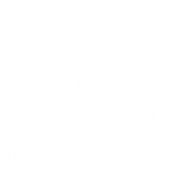Tidak semua kekerasan lahir di jalanan; sebagian tumbuh diam-diam di ruang kelas, sebagian lagi berakar di lingkungan rumah dan masyarakat. Perundungan di sekolah, tawuran antarwarga, atau perusakan fasilitas publik yang dipicu perbedaan keyakinan memperlihatkan rapuhnya keterampilan damai yang seharusnya ditanamkan sejak dini.
Awal tahun ajaran lalu, publik diguncang video perundungan di SMP Bandung yang memperlihatkan seorang siswa dipukul dan ditendang teman sekelasnya, sementara yang lain bersorak. Beberapa bulan kemudian, kasus serupa muncul di Cirebon dan kembali viral. Kekerasan tidak berhenti di sekolah; di ruang publik, kita juga berkali-kali menyaksikan bagaimana isu yang tak terkelola bisa memicu amuk massa dan merusak tatanan bersama.
Rangkaian peristiwa tersebut menegaskan satu hal: kita gagal melatih keterampilan damai sejak dini. Tanpa keberanian menjadikan toleransi sebagai praktik hidup dan bukan sekadar slogan, kekerasan akan terus berulang dari ruang kelas hingga ruang kebangsaan
Prasangka yang Tak Pernah Diurai
Di banyak sekolah, damai dan toleransi masih diajarkan sebagai hafalan, bukan keterampilan yang dihidupi. Murid bisa menyebut sila ketiga Pancasila, tetapi kesulitan menghargai teman yang berpakaian, berbicara, atau berpandangan berbeda. Prasangka tumbuh diam-diam, terbawa ke luar pagar sekolah, dan mewarnai interaksi di dunia nyata maupun maya.
Psikologi perkembangan menunjukkan mengapa kekerasan sering dipilih sebagai jalan keluar. Banyak anak tumbuh dengan keyakinan bahwa memukul atau melawan adalah cara wajar menyelesaikan masalah, pola yang kemudian terbawa hingga dewasa. Sikap mudah curiga membuat tindakan orang lain cepat ditafsirkan sebagai ancaman, sementara toleransi yang rendah terhadap ketidaknyamanan menjadikan perbedaan kecil terasa besar dan berbahaya.
Pola ini, jika dibiarkan, tak berhenti di masa anak-anak, tetapi terus akan berlanjut hingga dewasa. Perundungan di sekolah dapat menjelma menjadi diskriminasi di tempat kerja, perdebatan yang berubah menjadi ujaran kebencian di media sosial, atau kekerasan komunal di ruang publik.
Sekolah seharusnya menjadi benteng pertama memutus rantai ini. Namun, di banyak tempat, pendidikan damai berhenti di slogan. Nilai toleransi tercetak di buku teks, tetapi jarang dihidupkan dalam interaksi sehari-hari. Upacara bendera menggaungkan persatuan, tetapi di kantin masih ada meja-meja yang memisahkan “yang sama” dari “yang berbeda”. Kegiatan lintas identitas, kalaupun ada, sering hanya berupa kunjungan singkat tanpa tindak lanjut berarti.
Tanpa ruang aman untuk berlatih mengelola perbedaan, prasangka dari rumah dan lingkungan akan terus mengendap. Inilah yang membuat benteng sekolah rapuh menghadapi derasnya arus intoleransi di luar.
Tiga Lompatan Perubahan
Untuk memutus rantai kekerasan sejak dini, pendidikan damai perlu dihidupkan dalam praktik nyata. Ada setidaknya tiga langkah penting yang dapat ditempuh di sekolah.
Pertama, melatih siswa menunda penilaian terhadap situasi yang belum jelas. Dorong mereka belajar membaca ulang keadaan: apakah tatapan berarti marah atau sekadar lelah? Apakah komentar yang terdengar tajam dimaksudkan untuk merendahkan atau hanya bercanda? Latihan seperti ini dapat disisipkan di pelajaran Bahasa Indonesia melalui analisis tokoh cerita, atau di PPKn lewat studi kasus nyata. Tujuannya sederhana: menunda vonis, memberi ruang bagi kemungkinan lain, dan memilih respons yang menahan emosi.
Kedua, mengganti “kenalan sehari” dengan kerja sama nyata lintas kelompok. Alih-alih hanya berkunjung, siswa dari latar berbeda bekerja bersama dalam proyek yang menuntut saling bergantung, seperti membangun taman baca, membuat film pendek anti-perundungan, atau menggelar festival budaya sekolah. Dalam proses ini, perbedaan menjadi sumber kekuatan, bukan ancaman.
Ketiga, menerapkan pendekatan pemulihan hubungan secara terstruktur. Lingkar komunitas digunakan rutin untuk membangun keterbukaan, mediasi menangani gesekan kecil sebelum membesar, dan pertemuan pemulihan menyelesaikan kasus berat dengan rencana yang disepakati bersama. Pemulihan hubungan berjalan seiring dengan akuntabilitas.
Langkah-langkah ini hanya mungkin terwujud jika guru dibekali pelatihan, sekolah memiliki dukungan kebijakan, dan pendidikan damai dipandang sebagai prioritas setara dengan membaca, menulis, dan berhitung. Tanpa komitmen itu, nilai toleransi akan berhenti sebagai slogan indah yang terpajang di dinding sekolah.
Menjahit Ulang Ruang Kebangsaan
Pendidikan damai tidak bisa berhenti di sekolah. Inisiatif seperti Sahabat Sekolah Dasar, studi persahabatan antarsekolah, dan program Sahabat Belajar menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas latar dapat membentuk karakter. Jika diperluas dengan dukungan teknologi, praktik semacam ini dapat menjadi ruang belajar bersama yang menumbuhkan toleransi dan keberagaman.
Pengalaman nyata semacam ini lebih kuat daripada slogan seremonial, karena interaksi yang berulang melahirkan kebiasaan, dan kebiasaan membentuk budaya. Meski demikian, keberhasilan tetap harus diukur: survei iklim sekolah dapat memantau rasa aman dan empati, sistem pelaporan perundungan perlu sederhana dan cepat, dan proyek lintas identitas sebaiknya dinilai dari kualitas interaksi, bukan sekadar produk akhir.
Damai bukan sekadar tambahan, melainkan napas dari pendidikan kewarganegaraan di negeri yang majemuk. Setiap perundungan di sekolah, tawuran di jalanan, atau kerusuhan di ruang publik seharusnya membuat kita bertanya: nilai apa yang gagal kita tanamkan sejak awal?
Persatuan tidak akan tumbuh dari hafalan atau slogan, melainkan dari kebiasaan sederhana menghargai perbedaan, dilatih sejak kecil dan dipelihara sepanjang hidup. Jika ruang kelas mampu menjadi ladang bagi kebiasaan itu, maka dari sanalah lahir ruang kebangsaan yang lebih kokoh, bukan karena bebas dari perbedaan, tetapi karena mampu merawatnya.