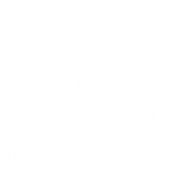Manajemen koalisi lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan telah menghasilkan suatu pemerintahan lebih stabil dalam lebih dua dekade terakhir di Indonesia. Namun, otokratisasi semakin kuat mengiringi tumbuhnya kekuasaan eksesif negara di bawah dominasi eksekutif. Bersama disfungsi lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif, pelemahan sistematis kekuatan sosial di luar negara menggerus daya resiliensi demokrasi.
Persekongkolan elite
Kesepahaman termasuk suatu kebutuhan dalam pengambilan putusan. Kegagalan untuk mencapai suatu kesepahaman dapat menciptakan kebuntuan, bahkan mungkin memunculkan konflik terbuka. Inilah yang terjadi pada 1950-an ketika antagonisme di antara kekuatan-kekuatan politik nasional tidak terjembatani dan pemerintah gagal untuk mengendalikan situasi secara efektif (Feith, 1962).
Sayangnya, Indonesia kemudian memilih untuk melemparkan demokrasi dan mengambil jalan otokrasi hingga kekuasaan Soeharto ambruk pada 1998. Pertarungan kepentingan antar-elite telah mempertaruhkan demokrasi dalam ketidakpastian. Pertentangan politik memaksa Abdurrahman Wahid, yang sebelumnya dipandang sebagai pemecah kebuntuan, untuk mengakhiri lebih awal kekuasaannya.
Ini seolah mengafirmasi kerentanan presidensialisme multipartai yang menimbulkan suatu kombinasi rumit bagi demokrasi (Mainwaring, 1993). Penguatan institusi presidensialisme kemudian dilakukan, antara lain melalui diperkenalkannya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden pada 2004. Manajemen lebih baik koalisi pemerintahan juga turut bekerja untuk menghasilkan stabilitas politik.
Distribusi sumber daya kekuasaan menjelaskan bertahannya Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono di kursi kepresidenan masing-masing pada periode berlainan. Akomodasi silang kepentingan di antara kekuatan-kekuatan utama politik telah mempermudah kesepahaman dan membuat pemerintahan berjalan lebih efektif. Namun, kompromi politik di antara mereka berdampak kemandekan demokrasi (Aspinall et al, 2015).
Pada masa berikutnya, Joko Widodo melengkapi politik distributif dengan pendekatan lebih koersif untuk menjamin keberlanjutan kekuasaannya. Berbagai bentuk intervensi terhadap partai-partai dia jalankan untuk menambah sekutu dan untuk memelihara loyalitas mereka; distribusi jabatan dan patronase negara dia manfaatkan pula untuk menjaga koherensi dalam koalisinya (Mietzner, 2016).
Dominasi eksekutif Jokowi dibangunnya dari kombinasi antara koalisi formal dan partai-partai dan koalisi informal dengan pelaku-pelaku lain. Pada relasi yang kedua, koalisi tersebut melingkupi mulai badan-badan negara dengan keistimewaan politik, seperti birokrasi, kepolisian, dan tentara; hingga pihak-pihak lain di luar negara, seperti kalangan oligark dan kelompok keagamaan (Mietzner, 2023).
Fabrikasi pembangunan dan kesan diri dekat dengan rakyat memberi Jokowi tambahan legitimasi. Dengan itu, berbagai inovasi otokratik Jokowi, seperti dalam operasi pencalonan putranya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden, secara ironis bisa mendapat dukungan luas publik. Bukan defisit kesepahaman antar-elite yang kini mengkhawatirkan, melainkan otokratisasi hasil persekongkolan di antara mereka.
Kekuasaan eksesif
Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintahannya merupakan pelanjut setia berbagai kebijakan Jokowi. Dalam konteks pembentukan koalisi, Prabowo menikmati pengaruh dan campur tangan Jokowi yang turut menentukan konstelasi politik seputar pemilu. Terkait manajemen koalisi, selanjutnya, Prabowo memanfaatkan secara efektif berbagai perangkat dalam rangka penguatan eksesif kekuasaannya.
Presiden memiliki, secara umum, sejumlah perangkat yang dapat diberdayakan untuk menambah dukungan dan untuk memperkuat pengaruh (Chaisty et al, 2018). Pertama, kuasa pembentukan kabinet. Distribusi posisi kementerian bagi partai-partai politik diharapkan dapat memperluas ruang kerja sama antara presiden dan DPR serta menjauhkan Prabowo dari kemungkinan pemakzulan.
Kedua, kewenangan anggaran. Perhatikan bahwa pemotongan anggaran atas nama efisiensi oleh pemerintahan Prabowo telah mengecualikan, antara lain, anggaran bagi DPR. Ini mempermudah dicapainya kesepahaman terkait perangkat ketiga, yaitu kekuasaan legislatif. Legislasi kilat dan tertutup UU TNI, misalnya, dapat dipahami dalam konstruksi pendayagunaan perangkat tersebut.
Keempat, kekuasaan partisan. Presiden dengan dukungan partai politiknya dapat mengambil putusan tertentu yang berbeda dari putusan para sekutunya tanpa mengorbankan koalisi. Kelima, pertukaran kepentingan. Di antara yang paling dikenal adalah distribusi patronase negara bagi elite partai, yang kini diberikan pula kepada organisasi kemasyarakatan dan kampus demi imbalan dukungan mereka.
Terdapat pola nyaris serupa, sejauh ini, terkait bagaimana Jokowi ataupun Prabowo memanfaatkan perangkat-perangkat kekuasaan tersebut untuk menghasilkan suatu dominasi eksekutif. Bedanya, intervensi koersif terhadap partai-partai politik tidak lagi mendesak untuk dilakukan; sebab, sebagai sekutu mereka telah menjadi terlalu kerdil di hadapan distribusi kuasa dan patronase negara.
Dominasi eksekutif berdampak terhadap kemerosotan fungsi-fungsi pada lembaga legislatif ataupun lembaga yudikatif. Ini membuka peran eksesif negara, termasuk melalui resentralisasi kuasa pemerintahan seiring politisasi birokrasi, kepolisian, dan tentara. Ketika hampir seluruh kekuatan di luar negara dilemahkan, dominasi bertopang persekongkolan elite tersebut hanya meneguhkan otokratisasi.
Kehadiran kekuatan oposisi yang solid sekaligus kredibel untuk menampik dominasi eksekutif merupakan bagian resep anti-otokratisasi. Namun, saat ini, meluapnya pragmatisme pengejaran kuasa di antara pelaku-pelaku politik justru memberi napas panjang bagi keberlangsungan rezim hibrida. Dalam situasi buruk tersebut, resiliensi demokrasi Indonesia menghadapi tantangan besar.
*Artikel telah dimuat di harian Kompas 8 April 2025.