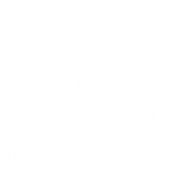”Apakah Reformasi telah mati” menjadi suatu pertanyaan relevan ketika kini demokrasi Indonesia terancam berbagai inovasi otokratik.
Ingatan kolektif tentang sejarah Reformasi dan gagasan pembaruan di dalamnya perlu disegarkan kembali. Langkah tersebut dapat menjadi bagian perlawanan terhadap otokratisasi agar kolektivitas politik tidak menjauh dari kebaikan bersama.
Reformasi telah mengakhiri kekuasaan otokratik Soeharto pada 1998. Rezim Orde Baru Soeharto ditandai struktur dan praktik politik yang memencilkan warga, terutama melalui represi, demi pemeliharaan kekuasaannya (Aspinall dan Fealy, 2010).
Tuntutan perubahan gradual dalam konteks politik, pemerintahan, dan hukum menjadi tumpuan dasar Reformasi sebagai suatu gerakan sosial.
Distorsi ingatan
Setelah ditolak oleh publik pada 2010 dan 2015, ironis bahwa kini Kementerian Sosial hendak mengusulkan kembali Soeharto sebagai seorang pahlawan nasional.
Asas kemanusiaan dan kerakyatan dinafikan begitu saja dalam rencana tersebut. Ingatan tentang perusakan kolektivitas politik di bawah kekuasaan Orde Baru ingin digerus oleh glorifikasi pembangunanisme Soeharto.
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa kekerasan 1998 itu tidak termasuk pelanggaran HAM berat sebelum dia menegasikan sendiri pernyataan tersebut.
Kebutuhan untuk menyegarkan ingatan kolektif tentang Reformasi dan untuk mewujudkan gagasan pembaruan di dalamnya menghadapi upaya sistematis untuk melupakannya.
Ingatan kolektif itu berakar, kata Jeffrey Barash (2017), dalam jaringan berlapis struktur simbolik yang berkelindan, menyebar, serta memberi acuan bagi kesadaran ruang-waktu dan logika konseptual suatu masyarakat.
Keberlanjutan jaringan itu bisa menguji keterkaitan antara masa lalu dan masa kini lewat cakrawala pengalaman yang bersemayam dalam kesadaran bersama lintas generasi.
Demokrasi dan kebebasan pasca-Soeharto berutang pada gerakan Reformasi.
Namun, kekuasaan negara menjalankan taktik ganda penjinakan untuk menciptakan dominasi dan ketundukan. Pertama, memutus keterkaitan sejarah dan merenggut kesadaran kolektif tentang gagasan pembaruan dalam Reformasi. Kedua, menjalankan teknik-teknik keras ataupun lunak untuk mempersempit kebebasan.
Penyuntingan secara selektif sejarah telah mendistorsi ingatan kolektif. Membentangkan jarak antara ingatan dan kebenaran, tindakan ini menyuntikkan lupa dan menghasilkan inkoherensi pengetahuan.
Pada saat yang sama, ruang kebebasan menyempit karena direnggut oleh kekuasaan negara melalui regulasi, represi, dan cara-cara lain yang lebih subtil sehingga menjadikan Indonesia semakin gelap.
Menyegarkan perlawanan
Selama dekade terakhir, kekuasaan eksekutif menguat secara eksesif diikuti oleh pelemahan akuntabilitasnya. Gerak berlawanan tersebut memberi pukulan mundur bagi Reformasi, yang mengusung kehendak demokratisasi.
Serangan terhadap demokrasi tersebut dapat diperiksa dari tiga aspek akuntabilitas pemerintahan: horizontal, diagonal, dan vertikal (Nord et al, 2025).
Merosotnya akuntabilitas horizontal ditandai oleh perluasan kendali eksekutif, menjadikan lembaga-lembaga lain negara lunglai. Persekongkolan antara eksekutif dan legislatif menghasilkan legalisme otokratik seiring melemahnya fungsi pengawasan DPR.
Lembaga peradilan mengalami pembusukan, ajudikasi menjauh dari keadilan. Sedangkan komisi-komisi negara kehilangan independensi mereka.
Setelah terhantam disrupsi, kapasitas kontrol civil society dan media massa melemah karena represi dan kooptasi yang dijalankan oleh negara sehingga memperburuk akuntabilitas diagonal pemerintah.
Akuntabilitas vertikal pun anjlok seturut dilemahkannya kapasitas sosial warga melalui pembatasan kebebasan dan model kebijakan pemberian bantuan yang mengarah penciptaan ketergantungan.
Melawan otokratisasi, naratif Reformasi itu kontekstual tidak semata dalam makna sejarahnya, yang kini telah menginjak usia 27 tahun dan terus dihantam distorsi. Lebih daripada itu, naratif yang sama memberi terang pada logika demokrasi.
Sebab, dalam tatanan otokrasi elektoral kini, para demagog banyak mengembangkan inovasi otokratik untuk menyamarkan represi di balik prosedur demokrasi.
Pemerintah bersama DPR kerap kali menjalankan legislasi secara kilat dan tertutup dengan muatan yang merugikan warga.
Manakala diprotes, mereka mempersilakan warga untuk mengajukan uji materi undang-undang; sementara, mereka berupaya sedemikian rupa untuk mengendalikan Mahkamah Konstitusi.
Memanggil ulang naratif Reformasi dalam bingkai sejarah yang statis akan hanya menjadikannya sebagai suatu monumen yang membatu.
Sebaliknya, menyegarkan naratif tersebut dalam konteks penampikan otokratisasi dapat mendorong suatu spirit progresif kewargaan yang berorientasi pada kebaikan bersama. Demikianlah suatu kolektivitas politik itu melingkupi, bukan malah memencilkan.
Legitimasi negara sebagai suatu kolektivitas politik itu terpelihara manakala otoritas di dalamnya melindungi kebebasan warga. Kebebasan itu turut membentuk kapasitas warga sebagai subyek yang berdaya.
Ketika kini terancam oleh otokratisasi, semangat kolektif untuk memulihkan kebebasan itu dapat menjadikan Reformasi suatu pengalaman yang kaya dan kontekstual bagi generasi berlainan.
Saya percaya Reformasi itu belum mati, tetapi arah pengelolaan negara saat ini jelas telah melenceng terlalu jauh dari kehendak untuk melembagakan demokrasi.
Bersama tekad untuk tindak ingin diringkus dalam otokrasi tertutup, ingatan kolektif tentang Reformasi itu tidak boleh padam dan harus terus lekat dengan upaya bersama untuk mengejawantahkan gagasan pembaruan di dalamnya.
*Artikel telah dimuat di harian Kompas 20 Mei 2025.