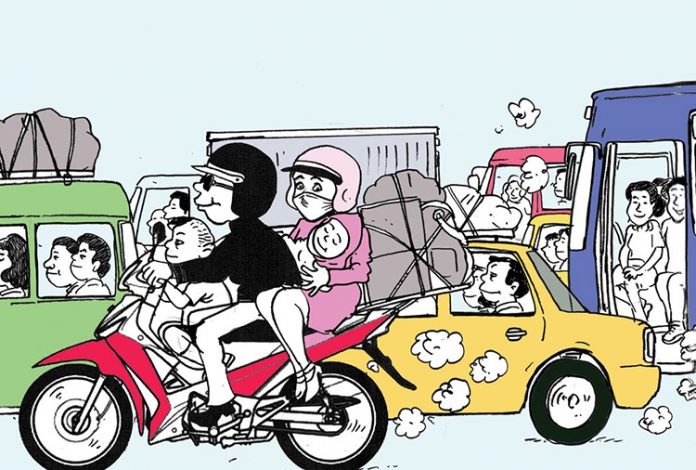Adakah saat yang paling dirindukan para pengembara selain menemukan momen kepulangan? Fakta keterlemparan manusia dari “langit suci” dan kebertualangan dari asal tumpah darah membuat sukmanya senantiasa resah-gelisah, merindukan luang berpulang ke rahim Ilahi dan kampung halaman.
Kesibukan mengejar kebutuhan dan kesenangan duniawi bisa membuat orang lupa diri sebagai perantau. Al-Ghazali mengibaratkan “materi” itu laksana kuda tunggangan bagi jiwa dalam pengembaraan jati dirinya. Sang jiwa harus memenuhi kebutuhan tunggangannya agar bisa mencapai tujuan. Namun, jika terlalu banyak menyita masa untuk memberi makan dan mengaguminya, sang jiwa mengantuk, tercecer di perjalanan, tak mencapai tujuan kepulangan.
Jeda puasa diharapkan bisa membuat sang jiwa siuman kembali. Buah dari kekhusyukan ibadah dan amal saleh adalah membersihkan kembali cermin hati, alat pemancar roh Ilahi. Hati yang bersih bisa memantulkan kembali cahaya Tuhan dan tumpuan manusia mengaca diri. Dengan mengaca diri, manusia bisa mengenali siapa dirinya; dari mana berasal dan ke mana berpulang.
Demikianlah, sepanjang tahun para perantau bergelut mengejar nikmat, berkah langit yang turun bak air hujan. Lewat penyadaran puasa, kedatangan Idul Fitri menjemput mereka kembali ke kelampauan asal spiritual dan sosial, seperti akar yang meneruskan air hujan ke sungai, lantas mengalirkannya hingga ufuk terjauh.
Seperti burung yang riang pulang ke sarang, kita rayakan kepulangan ke rahim fitri dengan sukacita. Kepulangan ini terasa lebih syahdu dengan senandung gema kebesaran Tuhan serta bingkisan bagi handai tolan. Setelah setahun menyerap hujan berkah langit, saatnya pengembara merembeskan air kebahagiaan bagi warga bumi agar akar rumput di segala pelosok negeri bangkit kembali dari kekeringannya.
Kebahagiaan terasa sempurna ketika kesuburan bumi terjaga berkat kerelaan berbagi. Al Quran melukiskan nafkah yang dibagikan ibarat sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dan setiap bulir berbuah seratus biji (QS. 2: 261). Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima, sehingga kesuburan dan kesejahteraan negeri bertambah.
Menurut Deepak Chopra, tubuh dan mental manusia senantiasa menjalin relasi saling memberi dan menerima dengan semesta. Mencipta, mencintai, dan menumbuhkan menjamin keberlangsungan relasi ini. Semakin banyak kita memberi makin terlibat dalam sirkulasi energi semesta; pada gilirannya semakin banyak kita peroleh dalam bentuk cinta, materi, dan ketenteraman.
Maka, jika kita memberi, berilah dengan senang hati. Jika hendak diberkati, berkatilah sesama dengan mengirimkan percikan pemikiran positif. Jika kita tak punya uang, berikanlah pelayanan. Kita tidak pernah kekurangan dalam apa yang dapat diberikan.
Semangat saling mengasihi, saling mengasah, dan saling mengasuh ini terasa kian penting saat kehidupan negeri dilanda banyak cobaan. Menjelang Idul Fitri, berbagai tanda kelesuan perekonomian, dekadensi politik dan kesusilaan membuat langit kejiwaan bangsa ini diselimuti mendung pesimisme.
Menghadapi kemungkinan musim paceklik berkepanjangan, yang kita perlukan bukanlah pesimisme atau optimisme yang buta. Kita harus bisa menggunakan pesimisme untuk menumbuhkan rasa keterpautan dengan realitas karena kesanggupannya untuk melihat situasi secara lebih akurat. Meski demikian, kita tak perlu hanyut dalam bayang-bayang kegelapan yang akan membuat kita terpenjara dalam ketidakberdayaan.
Lebaran harus menghadirkan optimisme mata terbuka bahwa tiap krisis mengandung peluang pembelajaran dan penyelesaian. Penyair Arab mengatakan, “Betapa banyak jalan keluar yang datang setelah kepahitan, dan betapa banyak kegembiraan datang setelah kesusahan. Siapa yang berbaik sangka kepada Pemilik Arasy, akan memetik manisnya buah yang dipetik dari pohon berduri.”
Optimisme yang produktif haruslah berjejak pada visi dan komitmen. Optimisme tanpa visi dan komitmen hanyalah lamunan kosong. Upaya menyemai optimisme harus memperkuat kembali visi yang mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, serta keampuhannya mengantisipasi masa depan. Visi ini harus menjadi kenyataan dengan memperkuat kapasitas transformatif kekuasaan, dengan mentalitas kepemimpinan yang lebar dan lebur.
Optimisme hendaklah bersifat realistis bahwa kegembiraan tidaklah datang dengan sendirinya tanpa dijemput, tanpa diusahakan dengan pengorbanan. Dalam gundukan sampah persoalan yang dihadapi bangsa saat ini, diperlukan persenyawaan jutaan titik embun untuk bisa menjadi gelombang kesucian yang bisa menyucikan najis kekotoran yang melumuri jiwa kenegaraan.
Dengan Idul Fitri, manusia mestinya bertobat (kembali) ke jalan fitrah (kemurnian asal kita sebagai manusia dan bangsa). Dengan hati suci yang bertaut dengan gelombang pertobatan kolektif, kita hadapi hadangan krisis dengan menguatkan integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
Tulisan ini telah diterbitkan di harian Kompas, 5 Juli 2016.