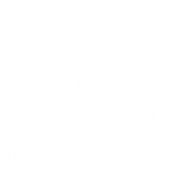Jaka, 27 tahun, bekerja di sebuah perusahaan rintisan di Jakarta. Setiap bulan, gajinya tersedot untuk biaya kos, cicilan motor, dan kiriman rutin ke orangtua di kampung. Tabungan? Nyaris mustahil. Mimpi memiliki rumah atau mempersiapkan pernikahan? Bagai fatamorgana: terlihat di kejauhan, tetapi terus menjauh ketika didekati. Kisah Jaka mewakili suara banyak anak muda yang hidup di ruang sempit antara penghasilan pas-pasan dan kebutuhan hidup yang terus membesar.
Delapan dekade lalu, Sukarno membayangkan kemerdekaan sebagai jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Bung Hatta menegaskan, kemerdekaan politik hanya berarti bila diiringi kemerdekaan ekonomi. Namun, di realitas hari ini, jembatan itu belum sepenuhnya mengantar generasi muda menjejak tanah cita-cita.
Data BPS per Februari 2025 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional berada di angka 4,76 persen. Namun, bagi mereka yang berusia 20–24 tahun, angkanya melonjak hingga sekitar 15,3 persen atau tiga kali lipat lebih tinggi. Kelompok usia 25–29 tahun pun tak jauh lebih baik, dengan TPT hampir dua kali lipat rata-rata nasional. Yang sudah bekerja pun tak selalu berada di posisi ideal: sekitar seperempat tenaga kerja hanya bekerja paruh waktu atau di bawah kapasitas keterampilannya, menandakan potensi produktivitas yang belum sepenuhnya terwujud.
Kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5 persen layak dicatat, tetapi tetap tertinggal di belakang laju kenaikan biaya hidup. Inflasi pangan kerap melampaui inflasi umum, sementara sewa hunian di kota-kota besar terus merayap naik, perlahan mengikis ruang aman bagi anak muda untuk menabung atau berinvestasi. Banyak yang terjebak dalam posisi sandwich generation—menopang diri sekaligus keluarga—hingga kemandirian finansial terasa seperti janji yang terus tertunda.
Simpul yang Mengikat
Persoalan ini tumbuh dari simpul-simpul yang saling menguatkan. Pertumbuhan ekonomi stabil (sekitar 5 persen per tahun) belum otomatis berbuah lapangan kerja berkualitas. Banyak peluang kerja yang tersedia bersifat sementara, berupah rendah, dan minim jalur pengembangan.
Sistem pendidikan pun masih terjebak dalam jurang antara teori dan praktik. Keterampilan kunci abad ini—literasi keuangan, penguasaan teknologi, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan—sering hanya menjadi pelengkap, bukan inti pembelajaran. Koneksi antara sekolah atau kampus dan dunia industri belum terbangun kokoh, membuat lulusan kerap gamang ketika harus menyeberang ke pasar kerja atau memulai usaha.
Kebijakan publik yang ada pun kerap terfragmentasi: pelatihan vokasi tanpa jalur penempatan, akses permodalan yang terhambat tanpa pendampingan, serta perumahan yang tetap di luar jangkauan pekerja pemula. Di sisi lain, arus budaya digital mendorong pola konsumsi instan: menukar ketahanan finansial jangka panjang dengan citra sukses sesaat.
Meretas Jalan
Jalan keluar terhadap persoalan di atas menuntut keberanian untuk membongkar ketimpangan yang menghambat, sekaligus membangun ekosistem baru yang memberi ruang bagi generasi muda untuk berkembang, berdaya, dan mandiri secara ekonomi.
Pertama, pendidikan harus menjadi arena pembebasan potensi, bukan sekadar pabrik pencetak tenaga kerja. Literasi keuangan, penguasaan teknologi, kreativitas, dan kewirausahaan perlu menjadi pilar utama, bukan pelengkap. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK (2024) mengingatkan, generasi muda Indonesia—meski akrab dengan teknologi—masih lemah dalam mengelola keuangan, sehingga rentan terjebak utang konsumtif, termasuk pinjaman daring. Pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi lintas disiplin, dan pengalaman lapangan yang otentik akan melahirkan generasi yang mampu mencipta pekerjaan, beradaptasi, sekaligus memimpin perubahan.
Kedua, dunia usaha perlu mendapat insentif strategis yang bersyarat: hanya bagi perusahaan yang melatih, merekrut, dan memberi upah layak kepada tenaga kerja muda dengan jenjang karier yang jelas. Model pendidikan ganda ala Jerman—memadukan pelatihan vokasi dengan magang berbayar—telah terbukti memperkecil kesenjangan keterampilan, dan bisa diadaptasi sesuai kebutuhan Indonesia.
Ketiga, akses modal mesti dibarengi pendampingan yang berkelanjutan. Pengalaman internasional, dari Grameen Bank di Bangladesh hingga Youth Business International di berbagai negara, menunjukkan bahwa modal yang disertai bimbingan mampu meningkatkan kelangsungan usaha secara signifikan. Skema pembiayaan mikro berbunga wajar, dipadu akses pasar digital dan dukungan mentor aktif, akan memberi napas panjang bagi wirausaha muda.
Keempat, kebijakan perumahan progresif harus menjadi prioritas. Subsidi uang muka KPR, pengembangan hunian terjangkau di dekat pusat ekonomi, atau skema rent-to-own dapat menjadi pijakan finansial yang kokoh, memberi rasa aman untuk membangun masa depan.
Terakhir, percepatan transformasi digital tak lagi bisa ditunda. Infrastruktur internet yang merata, pelatihan e-commerce, dan ekosistem teknologi yang ramah pemula dapat menjadi pengungkit pertumbuhan. Riset Litbang Kompas bersama Grab Indonesia (2022) membuktikan, UMKM yang bertransformasi digital selama pandemi mencatat pertumbuhan omzet signifikan—banyak di antaranya digerakkan oleh perempuan Gen Z.
Menepati Janji
Kemerdekaan ekonomi tidak akan datang sebagai hadiah, melainkan harus diperjuangkan melalui kebijakan yang berpihak, pendidikan yang membebaskan, dan kesadaran kolektif bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana anak mudanya dapat berdiri tegak secara finansial.
Delapan dekade lalu, para pendiri republik membangun jembatan emas. Kini, tugas kita memastikan jembatan itu benar-benar mengantar generasi muda menapaki tanah yang dijanjikan—bukan sekadar melihatnya dari kejauhan.