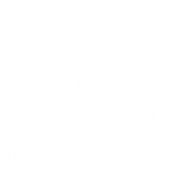Sudah bertahun-tahun kita disuguhi laporan tentang rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Data UNESCO yang sering dikutip menunjukkan indeks minat baca kita hanya 0,001. Dengan kata lain, hanya satu dari seribu orang Indonesia yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai pembaca sejati.
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 pun menunjukkan hal serupa: kemampuan literasi anak-anak Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan rata-rata negara OECD.
Kondisi ini memunculkan berbagai program literasi, baik dari pemerintah maupun sekolah. Buku-buku didistribusikan, perpustakaan dibangun, kegiatan membaca 15 menit sebelum belajar digalakkan. Semua upaya itu penting, tetapi pertanyaan mendasar tetap ada: mengapa setelah bertahun-tahun program literasi berjalan, kita masih gagal melahirkan pembaca sejati?
Jawaban singkatnya: karena kita lebih sibuk mengajarkan membaca sebagai kewajiban ketimbang menumbuhkan membaca sebagai kebutuhan. Anak-anak membaca karena disuruh, bukan karena ingin.
Literasi yang Bersifat Seremonial
Program literasi di sekolah sering kali berhenti pada ritual administratif. Anak diminta membuka buku, membaca, lalu mencatat. Targetnya jelas: ada bukti tertulis bahwa kegiatan membaca sudah berlangsung. Namun, apakah dari situ lahir kecintaan pada bacaan? Sering kali tidak.
Di rumah, orangtua pun sering menjadikan membaca sebagai beban moral: “bacalah supaya pintar” atau “jangan main ponsel terus, coba baca buku.” Alih-alih membangkitkan minat, cara ini justru memperkuat kesan bahwa membaca adalah aktivitas wajib yang membosankan.
Tanpa dorongan dari dalam diri, buku hanya akan dilihat sebagai beban. Padahal, membaca baru akan menjadi kebiasaan bila lahir dari dorongan alami: rasa ingin tahu.
Keingintahuan yang Terlupakan
Inilah letak kelemahan mendasar program literasi kita: tidak ada strategi serius untuk memupuk keingintahuan.
Dalam praktik pendidikan, kita lebih menghargai anak yang bisa menjawab pertanyaan dengan tepat daripada anak yang berani bertanya. Padahal, pertanyaan adalah tanda keterlibatan, tanda bahwa pikiran sedang bekerja. Romo Mangun pernah mengingatkan, ukuran kecerdasan seharusnya bukan seberapa banyak anak bisa menjawab, melainkan seberapa tajam pertanyaan yang ia ajukan.
Kita hidup di era banjir informasi. Data tersedia di ujung jari, tinggal satu klik. Dalam situasi ini, kemampuan mengajukan pertanyaan justru jauh lebih penting daripada sekadar menghafal fakta. Tanpa pertanyaan, informasi berlimpah hanya akan membuat bingung.
Sayangnya, keingintahuan anak-anak sering kali dipatahkan sejak dini. Pertanyaan mereka dianggap cerewet, mengganggu, atau merepotkan. Di kelas, guru jarang memberi ruang eksplorasi. Di rumah, orang tua sibuk dengan gawai. Akibatnya, anak-anak tumbuh dengan kesadaran bahwa bertanya bukan sesuatu yang dihargai.
Membaca karena Ingin, bukan karena Disuruh
Craig Wright dalam The Hidden Habits of Genius menyebut gairah belajar sebagai ciri utama orang-orang jenius. Mereka terus membaca, meneliti, dan bereksperimen karena selalu dihantui pertanyaan. Rasa ingin tahu itulah yang mendorong mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Sebaliknya, banyak akademisi kita berhenti membaca begitu meraih gelar atau jabatan. Seorang dosen pernah berkeluh kesah bahwa tak sedikit profesor merasa tidak perlu lagi membuka jurnal terbaru. Pada saat mereka kehilangan keingintahuan, di situlah mereka juga berhenti tumbuh sebagai pembelajar.
Inilah bedanya antara sekadar bisa membaca dan menjadi pembaca sejati. Pembaca sejati tidak membaca karena diwajibkan. Mereka membaca karena ingin tahu, karena haus pengetahuan. Dan semakin banyak membaca, semakin mereka sadar betapa banyak yang belum mereka ketahui. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati dan semangat untuk terus mencari.
Jalan ke Depan
Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya bukan sekadar menambah buku atau mengatur jam wajib baca, melainkan membangun ekosistem keingintahuan.
Pertama, mulai dari rumah. Orangtua perlu membiasakan diri menjawab atau menanggapi pertanyaan anak, betapa pun sederhananya. Pertanyaan adalah tanda hidupnya pikiran.
Kedua, sekolah harus bertransformasi dari ruang transfer pengetahuan menjadi ruang eksplorasi. Guru tidak hanya memberi jawaban, tetapi juga melatih murid mencari sendiri. Pemberian bacaan pun sebaiknya relevan dengan dunia anak, bukan sekadar daftar wajib.
Ketiga, ruang publik perlu lebih banyak menyediakan forum diskusi, klub baca, dan percakapan intelektual. Budaya bertanya dan mencari harus dirayakan, bukan dipandang aneh.
Program literasi yang hanya menekankan aspek teknis membaca tak akan pernah cukup. Buku bisa dikirim, perpustakaan bisa dibangun, jam baca bisa diwajibkan. Tapi tanpa rasa ingin tahu, semua itu hanya akan jadi ritual kosong.
Membaca Bukan Ritual, tetapi Jalan Hidup
Program literasi kita kerap gagal menumbuhkan pembaca sejati karena mengabaikan satu hal yang paling sederhana sekaligus mendasar: keingintahuan.
Tanpa keingintahuan, membaca hanyalah aktivitas mekanis yang mudah dilupakan begitu kewajiban usai. Dengan keingintahuan, membaca menjelma menjadi perjalanan hidup yang membuka cakrawala, memperdalam batin, dan menumbuhkan cinta pada pengetahuan.
Jika kita sungguh ingin membangun bangsa pembelajar, titik awalnya bukan pada tumpukan buku atau kewajiban membaca, melainkan pada upaya menyalakan rasa ingin tahu. Sebab, pertanyaan selalu menjadi pintu, dan buku akan senantiasa menjadi jalan.