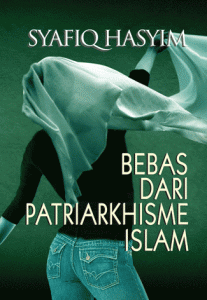 DATA BUKU
DATA BUKU
Judul : Bebas Dari Patriarkhisme Islam
Penulis : Syafiq Hasyim
Cetakan : 1, Juli 2010
Penerbit : Kata Kita, Depok
Tebal : 442 halaman
ISBN : 978-979-3778-62-4
Kata patriarkhisme menjadi momok bagi kalangan perempuan. Pasalnya, budaya patriarkhisme menjadi penyebab utama dari ketidakadilan bagi perempuan. Apalagi ketika patriarkhisme merasuk ke dalam agama Islam, akan timbul kesan Islam berlaku tidak adil terhadap perempuan. Buku setebal 442 halaman ini mengupas bagaimana keterkaitan Islam dan patriarkhisme serta berupaya membebaskan Islam dari paham-paham patriarkhisme yang seakan ‘menempel’ pada Islam.
Buku yang berjudul Bebas Dari Patriarkhisme Islam (2010) karya Syafiq Hasyim secara garis besar mengupas mengenai Islam, perempuan, dan quo vadis gerakan; perempuan sebagai korban dari patriarkhisme Islam; serta perempuan dan ruang pembebasan.
Di awal, Syafiq Hasyim membawa pembaca pada hakikat Islam. Sejatinya Islam diturunkan untuk membebaskan manusia dari keterkungkungan dan ketertindasan umat manusia lainnya (h. 53). Artinya tidak mungkin Islam menolelir adanya ketidakadilan yang dialami umatnya, terutama pada perempuan.
Hal ini, sebab Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya penghormatan terhadap manusia dan itu terlihat dari ajarannya yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan manusia. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas takwanya sebagaimana tercermin dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13.
Namun, realitasnya penindasan terhadap kaum perempuan terus terjadi. Padahal, kemunculan Islam secara hakiki membawa pesan-pesan keadilan dan kesetaraan bagi umatnya. Jika demikian, jelaslah ketidakadilan terhadap perempuan bukan muncul dari agama melainkan budaya patriarkhi yang bercokol di masyarakat dan mengkontaminasi Islam. Makanya, sulit jika terjadi peleburan antara adat dan agama yang secara bersama-sama melawan konsep kesetaraan terhadap perempuan (h. 38)
Menganggapi hal itu, Abdoulkarim Soroush seorang intelektual Iran berpendapat harus ada kejelasan antara keagamaan (religion) dan pengetahuan terhadap keagamaan (religion knowledge) (h. 150). Karena sesungguhnya menurut Farida Benani teks (baca: al-Qur’an) tidak bisa berucap sendiri, tidak menjelaskan sendiri, tidak memotong apa yang ada di dalamnya, dan tidak merupakan fenomena yang hidup untuk menjelaskan makna dan apa yang dikehendakinya oleh dirinya sendiri, maka perkara yang tepat untuk hal ini adalah menafsirkannya (h. 149). Dari dua pernyataan tersebut menunjukan apa yang selama ini dipahami dalam masyarakat Muslim adalah hasil dari tafsiran para ulama terhadap teks. Sayangnya, tafsiran tersebut tidak membawa pesan yang egaliter.
Berbagai persoalan yang menimpa perempuan membuktikan hal tersebut. Contohnya, kekerasan terhadap perempuan yang terkesan dilegalkan oleh Islam, seperti dalam kasus nusyuz. Suami berhak memukul istrinya apabila dianggap melakukan pembangkangan (h. 151). Atau khitan yang dilakukan saat remaja putri yang menginjak baligh (dewasa) atau masih kecil dengan alasan mengurangi hawa nafsunya (h. 159). Juga domestifikasi perempuan dengan melarang perempuan melangkahkan kaki ke luar rumahnya dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, dan tubuhnya dianggap aurat sehingga harus ditutup seluruhnya serta pelbagai persoalan lainnya (h. 161).
Perbuatan-perbuatan demikian sesungguhnya keliru. Pada zaman Nabi Muhammad, perempuan mendapat berbagai keistimewaan. Dengan bebas perempuan boleh bertanya bahkan menggugat persoalan kepada Nabi, seperti yang dicatat oleh Ruth Roded bahwa ada sekitar seribu dua ratus orang yang berhubungan langsung dengan Nabi diantara beribu-ribu sahabat Nabi (h. 92). Ini menandakan bahwa Nabi pun mendengar suara-suara perempuan. Nabi tak abai dengan persoalan perempuan bahkan justru Nabi berusaha untuk mencari solusi bagi umatnya. Hanya saja, tradisi ini pudar seiring dengan tahun-tahun kematian nabi, pada zaman Umar bin Khattab sebagai Khalifah perlakuan yang membebaskan perempuan cenderung menurun. Terlebih pada masa Bani Abbasyiah dan Ummayah, pada masa itu lelaki boleh memiliki ribuan budak.
Leila Ahmed menyebutkan praktik dan sikap kebangsawanan Abbasyiah banyak diadopsi dari bangsawan Sasanid. Pada masa itu Khalifah Mutawakkil memiliki empat ribu budak dan Khalifah Harun al-Rasyid memiliki beribu-ribu budak (h. 95). Ini secara langsung memperlihatkan kemunduran Islam dalam berlaku keadilan terhadap perempuan. Keadaan ini terus berlangsung sehingga membuat gusar para pemikir Islam kontemporer.
Merespon persoalan tersebut, munculah apa yang disebut dengan gerakan perempuan atau tahrir al mar’ah yang dipelopori oleh intektual islam kontemporer di Mesir, Turki, dan Syiria. Terbitlah nama-nama seperti Rifa’ah Tahtawi intelektual mesir pertama yang mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya dalam mengkaji persoalan perempuan, dilanjutkan dengan Qasim Amin, Malak Hafni Nasif dan pemikir pemikir lainnya. Juga seperti pemikir Maroko seperti Fatima Mernissi, atau Amina Wadud, Asma Barlas, Haideh Moghissi dan sejumlah pemikir yang lain. (h. 343)
Selain itu yang menarik adalah terlibatnya laki-laki dalam mewacanakan persoalan perempuan. Ulama laki-laki turut andil dalam membebaskan wacana Islam dalam kungkungan budaya patriariarkhi. Sebutlah KH. Hussein Muhammad, KH. Muhyiddin Abdushomad, KH. Masdar F. Mas’udi, dan Nassaruddin Umar yang giat mengkampanyekan isu perempuan baik di pesantren maupun dalam masyarakat luas (h. 399-407).
Barat, Laki-laki dan Islam
Setidaknya ada tiga hal yang hendak dibongkar balam buku ini. Pertama, anggapan khalayak publik mengatakan bahwa wacana gender (baca: persoalan perempuan) adalah produk Barat. Kedua, wacana gender bukanlah bagian diskursus Islam. Ketiga, dan karena itu wacana gender hanya pantas dibicarakan oleh kalangan perempuan saja. Namun secara perlahan ketiga hal itu dipreteli dalam buku ini.
Pertama, memang harus diakui masuknya isu gender dalam kawasan Islam tidaklah bebas dari pengaruh Barat, seperti Rifa’ah Tahtawi fokus kepada persoalan perempuan setelah selesai pendidikan di Prancis, pun dengan Qasim Amin, dan Ali Syariati yang mendapat pengaruh yang sama yaitu setelah memperoleh pendidikan dari Barat. Namun perlu digarisbawahi adalah para intelektual islam tersebut tidak serta merta menelan mentah-mentah isu gender. Justru mereka mengambil semangat keadilan gender dengan kembali mengkaji al-Qur’an dan sunnah. Mereka tak segan-segan mengkritik perempuan barat yang terjebak dalam kapitalisme global, seperti yang dilakukan oleh Ali Syariati. Berbekal keyakinan bahwa islam sebagai agama yang egaliter kemudian mereka melakukan pembaharuan dalam pengetahuan Islam. Sehingga, citra islam sebagai agama yang patriarkhal dapat luntur.
Kedua, banyak pula yang menyangka bahwa membahas mengenai isu gender dianggap tidak Islami. Berdasarkan pengalaman beberapa aktivis perempuan, ketika membincang soal gender maka langsung muncul anggapan bahwa aktivis tersebut liberal, bukan muslim 24 karat dan tidak kaffah dalam menjalankan keislamannya. Justru mereka mencoba mengkampanyekan Islam yang ramah terhadap perempuan, bukan Islam yang hanya mampu membatasi perempuan, dan melakukan diskriminasi perempuan. Seperti halnya Nabi Muhammad yang sangat memperhatikan nasib perempuan dan melakukan revolusi pemikiran dalam memandang perempuan.
Ketiga, soal keterlibatan laki-laki dalam mewacanakan isu gender. Di Mesir ada cendikiawan muslim seperti Rifa’ah Tahtawi dan Qasim Amin; di Iran ada seorang Ali Syariati dan Ayatullah Murtazha Muthahhari; di Indonesia nama-nama semisal KH. Hussein Muhammad, KH. Muhyiddin Abdushomad, KH. Masdar F. Mas’udi, dan Nassaruddin Umar adalah ulama-intelektual laki-laki yang konsern dalam membahas persoalan persoalan perempuan.
Jadi keterlibatan laki-laki dalam membahas isu gender setidaknya akan membongkar stigma bahwa laki-laki hanya mampu menjadi pelaku kekerasan, melainkan bisa menjadi partner perempuan dalam mengkampanyekan persoalan gender. Keterlibatan juga akan mengubah pandangan bahwa persoalan perempuan adalah tanggung jawab masyarakat bukan hanya urusan perempuan semata. Tentu dengan keterlibatan semua pihak, persoalan perempuan dapat diatasi dengan baik. Meskipun pada akhirnya penulis mendorong perempuan untuk muncul menjadi ulama yang memiliki otoritas dan kredibilitas yang sama dengan ulama laki-laki.

