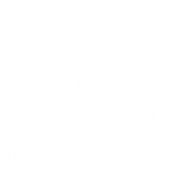Delapan puluh tahun telah berlalu sejak Bung Karno berpidato di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan pada 1 Juni 1945. Di tengah suasana penjajahan yang menggoreskan luka dan harapan dalam satu tarikan napas, ia menggali dari kedalaman tanah dan jiwa Nusantara satu pusaka nilai yang disarikan menjadi Pancasila.
Di jantung kelima sila Pancasila tersebut berdetak jiwa gotong royong yang memompa darah sehat—menghidupi semangat kolektif yang menjadi penopang utama keberlangsungan bangsa ini. Gotong royong bukan sekadar kerja bersama. Ia adalah cara bangsa ini merawat luka, menganyam harapan dan mengatasi keterbatasan dalam peluk kebersamaan.
Ia tumbuh dari akar-akar budaya yang menjalar dalam sejarah ribuan tahun ketika gugus-gugus manusia kepulauan ini mengangkat batu besar, mendirikan lumbung pangan, menggali irigasi, dan mengayuh bahtera bersama, bukan karena perintah, tetapi karena panggilan nurani kolektif.
Ajaibnya, delapan dekade setelah Pancasila dipidatokan sebagai dasar negara, watak dasar komunitas bangsa ini belum pudar. Dalam riset mutakhir yang dilakukan oleh Harvard Human Flourishing Program, Indonesia tercatat sebagai negara paling flourishing—paling berkembang dalam arti kesejahteraan holistik, bukan sekadar ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual.
Hasil tersebut tentu mengejutkan banyak kalangan: bagaimana mungkin negara dengan beragam tantangan sosial, politik, dan ekonomi menempati peringkat tertinggi dalam hal kesejahteraan hidup manusia?
Kunci jawabannya, kata para peneliti, terletak pada kekuatan jalinan sosial: kebersamaan, rasa saling percaya, serta kehangatan komunitas yang menjadi penyangga emosi dan harapan warganya.
Gotong royong, yang sering kali hanya menjadi jargon politik, ternyata hidup nyata di lorong-lorong kampung, di dapur umum saat bencana, di celengan tempat-tempat ibadah, di sistem arisan dan ronda, di mana warga bekerja untuk warga, bukan untuk keuntungan.
Konfirmasi atas hal ini datang pula dari World Giving Index yang selama beberapa tahun terakhir menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Bukan negara kaya. Bukan pula negara yang sistem kesejahteraannya sudah sempurna. Tetapi, negara yang masyarakatnya, dalam segala kekurangannya, tetap memilih untuk memberi.
Memberi uang, waktu, tenaga, bahkan empati. Ini adalah wujud dari Pancasila yang berjalan tanpa dipaksa. Sebuah keajaiban moral di tengah dunia yang makin individualistik.
Bahasa Indonesia pun menjadi saksi lain dari keajaiban gotong royong ini. Ia lahir bukan dari pusat kekuasaan, bukan pula berasal dari bahasa penjajah atau kelompok dominan.
Bahasa ini tumbuh dari pertemuan budaya yang mengalir bebas: dari bahasa Melayu pesisir, diperkaya perbendaharaan Buddha Sriwijaya, jaringan keilmuan, kekuasaan, dan perdagangan komunitas Islam, jejak Latin dan Portugis, resonansi misi Kristen dan terjemahan Alkitab, artikulasi jurnalistik pers Tionghoa abad ke-19, serta didukung peran agen-agen komunitas lainnya.
Ia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sebagai simbol persatuan yang lahir dari keragaman.
Bahasa Indonesia kini menjadi penopang persatuan nasional sekaligus wahana kemajuan ilmu, seni, dan diplomasi. Diakui UNESCO sebagai bahasa resmi sidang umum, ia menunjukkan vitalitas global.
Studi linguistik juga menempatkannya sebagai salah satu bahasa paling bahagia di dunia. Dalam struktur katanya, dalam idiom dan iramanya, ia memantulkan semangat hidup yang penuh harap, bahkan ketika kenyataan tak selalu menggembirakan.
Ironi Indonesia
Ironisnya, pusaka nilai yang luhur itu lebih tumbuh kuat dan sehat di jantung kehidupan komunitas, tetapi belum cukup meresap ke ranah politik-kenegaraan—dengan segala implikasi negatifnya bagi persatuan dan keadilan.
Di tengah warga, gotong royong hadir dalam semangat silih asih (saling mencintai), silih asah (saling mewaraskan), silih asuh (saling membimbing).
Tatkala nilai itu memasuki ranah politik, wujudnya perlahan berubah. Apa yang di kampung-kampung tumbuh sebagai kemurahan hati, di gedung-gedung parlemen kerap menjelma menjadi kompromi penuh kalkulasi.
Yang semula mengikat warga dalam kebersamaan yang menyehatkan, beralih rupa menjadi transaksi kepentingan yang membusukkan. Gotong royong yang sejatinya mencerminkan cinta konstruktif, menjelma menjadi gotong-royong yang sungsang: korupsi berjamaah, politik akomodasi, dan aliansi oportunistik demi ambisi kekuasaan.
Seolah menjadi ironi sejarah Indonesia: komunitas yang sehat dalam negara yang sakit. Di tengah masyarakat yang masih menyimpan kearifan kolektif dan semangat saling jaga, negara justru kehilangan arah etik dalam mengelola kekuasaan. Akar budaya warga belum menemukan kanal politik yang mampu menyalurkannya.
Nilai-nilai luhur yang hidup di lorong kampung belum menjelma menjadi roh dalam pengambilan keputusan. Demokrasi prosedural yang kita anut berjalan dalam bentuk, tetapi kerap kosong isi—hadir dalam mekanisme, tetapi absen dalam semangat.
Maka, lahirlah negara yang limbung, terputus dari jiwa rakyatnya, terjebak dalam logika kuasa yang hampa makna.
Partai politik, misalnya, tak lagi menjadi wahana perjuangan aspirasi dan aksi kolektif. Ia telah menjelma menjadi semacam perusahaan privat yang dikendalikan oleh segelintir orang kuat.
Sistem perwakilan yang semestinya menjadi jembatan bagi keragaman kebangsaan kini cenderung tereduksi menjadi kontestasi perwakilan individual, tanpa menjamin kehadiran wakil golongan marjinal dan unsur strategis bangsa, maupun representasi sejati dari basis-basis komunitas kedaerahan.
Demokrasi pun kehilangan daya wakilnya—terperangkap dalam mekanisme elektoral yang menjauh dari semangat gotong royong yang positif.
Keputusan politik kerap lahir tergesa, dibayangi semangat mayoritarianisme yang lebih menonjolkan unjuk kekuatan ketimbang merawat kebijaksanaan kolektif. Musyawarah-mufakat—nadi demokrasi gotong-royong—perlahan ditinggalkan, digantikan oleh voting yang cepat tetapi dangkal.
Suara minoritas kurang dihargai; pandangan yang berbeda dianggap sebagai gangguan, alih-alih penyeimbang. Aspirasi akar rumput tersisih oleh pemaksaan elite, yang lebih sibuk menghitung kalkulasi kuasa daripada membangun kesepahaman.
Demokrasi yang semestinya tumbuh dari percakapan, perjumpaan, dan pertukaran gagasan justru menyusut menjadi perlombaan angka nirsubstansi.
Sistem perencanaan pembangunan di negara ini pun kian menjauh dari semangat gotong royong.
Haluan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) cenderung berpusat pada kepentingan cabang eksekutif, tanpa cukup membuka ruang bagi aspirasi cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Orientasi pembangunannya lebih banyak ditentukan oleh logika birokrasi negara, sementara partisipasi masyarakat sipil dan dunia usaha belum mendapat tempat yang layak. Arah kebijakan pun masih kuat didikte oleh kepentingan ekonomi semata sehingga dimensi sosial, budaya, lingkungan, dan spiritualitas kerap dipinggirkan.
Di sisi lain, karena presiden juga memegang peran dalam proses legislasi, pelaksanaan RPJPN kerap dibayangi oleh agenda elektoral, menjadikan kebutuhan strategis bangsa rawan disubordinasikan oleh kalkulasi politik jangka pendek. Dalam lanskap seperti ini, semangat pembangunan sebagai usaha gotong royong seluruh anak bangsa kehilangan wahana pelembagaannya.
Dalam konteks inilah kita mesti jujur mengakui: Pancasila, yang diagungkan sebagai dasar dan ideologi negara belum sungguh-sungguh menjiwai praktik demokrasi dan tata kelola negara. Ia megah di mimbar, tetapi kerap absen dalam keputusan strategis.
Dipuja sebagai simbol, tetapi menguap dalam kelembagaan dan kebijakan. Alih-alih menjadi penuntun arah, Pancasila terkurung dalam retorika tanpa daya gerak. Padahal, yang kita dibutuhkan bukan sekadar slogan, melainkan roh yang menghidupkan hukum, lembaga, sistem perwakilan dan keputusan.
Bila terus menggantung sebagai slogan, tanpa mendarat di bumi, Pancasila kehilangan daya cipta, dan kita pun kehilangan arah.