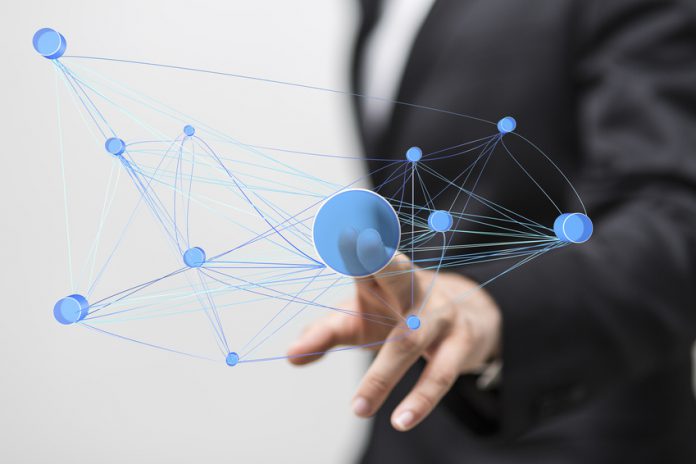’…menyaksikan zaman gila, serba susah dalam bertindak, ikut gila tak akan bertahan, tetapi kalau tidak mengikuti (dalam kegilaan), tak akan mendapat bagian, kelaparan pada akhirnya….’ (Ranggawarsita, dalam Serat Kalatidha)
Indonesia merupakan negeri yang paradoks dan anakronik. Di satu sisi,negeri ini memiliki kekayaan alam yang amat melimpah ruah, yakni hutan dan lautan yang luasnya sejauh mata memandang. Namun, di sisi lain, secara bersamaan,terdapat sejumlah penyakit sosial yang mengakar merambah ke sendi-sendi kehidupan masyarakat kita yang secara langsung memberikan dampak negatif terhadap mentalitas dan etos kerja bangsa ini ke depan.
Merebaknya wabah penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD), flu burung, chikungunya adalah perpanjangan tangan dari penyakit sosial yang melanda negeri ini. Bahkan, kondisi ini telah masuk pada level frustrasi dan hilangnya rasionalitas watak dan mental kita. Lihat saja, di mana-mana terjadi kekerasan mulai komunitas terkecil (keluarga) bunuh diri sekeluarga hingga kekerasan dalam ruang pendidikan.
Padahal, ini aset masa depan negeri ini. Belum lagi tempat tinggal yang tergusur dan terusir oleh kecerobohan dan ketamakan segelintir orang. Hingga kapan nasib mereka akan terus seperti ini? Untuk inikah mereka menyandang identitas keindonesiaan? Apa yang salah? Siapa yang salah? Apa kesalahan kita? Itu semua sederet pertanyaan yang sulit sekali menemukan jawaban yang tepat dan tuntas. Apakah penguasa yang bersalah
Penguasa tidak pernah mau dipersalahkan sedikit pun. Mereka berada pada satu titik, yakni imunitas ada pada mereka. Ada komunitas ’’The untouchable’’ dalam ruang kenegaraan dan kebangsaan. Lantas,apakah rakyat yang bersalah? Memang,amat biasa kita dengan mudah memosisikan rakyat secara tidak adil. Itu sesuatu yang lumrah. Kadang, penguasa tidak mau ambil pusing dengan kepusingan rakyat kecil dalam mengurusi rumitnya kehidupan sehari-hari.
Tampaknya, penguasa tidak secara sungguh-sungguh mengambil bagian secara jujur dalam meringankan penderitaan rakyat yang terkucil pada ruang-ruang kemiskinan dan kemelaratan.
Hilangnya Dimensi Kenegaraan
Intuisi sosial dapat menemukan sebuah realitas memedihkan ketika formalisasi sosial politik tidak berjalan dalam wilayah kesadaran, mentalitas dan kultur hidup. Pengarusutamaan demokrasi hanya bersifat material, formalistik, dan institusionalistik.
Proses-proses itu berada dalam genggaman pemilik kekuasaan. Anonimitas publik terhadap proses-proses demokrasi amat kentara dalam sesi politik saat ini. Ada sebuah mitos sosial politik. Sesi-sesi demokratisasi dan transformasi politik tumpang-tindih secara kasar dengan kekejian maniak kekuasaan. Walhasil, performa politik kekuasaan, yang disucikan label demokrasi, hanya bertahan dalam hitungan bulan.
Selebihnya, sarat retorika, propaganda, dan konsolidasi kroni politik, menuju perang politik edisi berikut. Kerinduan sosial politik publik tidak pernah bersandar pada kepastian. Ternyata, lingkaran dalam kekuasaan tidak tersentuh suka cita publik dalam melahirkan kembali Indonesia.
Banyak pihak yang merasa tidak perlu melibatkan diri dalam ziarah kultural suci ini. Sedemikian keji, Indonesia tidak lagi menjadi medium peradaban dan entitas sosial politik raksasa yang dapat melabuhkan masyarakat pada kemakmuran dan kesejahteraan. Esensi keindonesiaan tidak pernah ada pada titik itu. Kelihaian politik mereduksikan keindonesiaan sekadar menjadikannya benda yang memuaskan dahaga kerakusan dan amat sering menciptakan kecelakaan memedihkan.
Sebagian orang telah merobek keindonesiaan dan merendahkan kebangsaan ini sebagai alat yang memuaskan segudang nafsu tak terpuaskan. Bangsa ini menciut menjadi arena pertarungan merebut kesempatan memperkaya diri, memenuhkan lumbung ketamakan, dan mencuci kotoran menjijikkan dengan mekanisme yuridis yang bisa dibeli dengan uang.
Pantas kiranya ramalan seorang pujangga besar Jawa Ranggawarsita sebagaimana kutipan di atas dengan kondisi negeri kita saat ini. Berjalan lurus, menjadi orang jujur di tengah-tengah kebobrokan adalah sebuah kegilaan. Tendensi semacam ini telah kelihatan dalam penampilan budaya politik dalam era ’’kebebasan yang bablas’’ ini. Indonesia berjalan tanpa roh.
Yang sedang menggerakkan Indonesia adalah bisingnya segudang kepentingan segelintir orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan.Kerakusan tanpa batas, ketamakan tanpa akhir,kedurjanaan tanpa sesal, memacetkan energi keindonesiaan dalam menyentuh level keadaban manusiawi.
Indonesia Baru Jilid III
Sungguh tepat kiranya jika kita berani menabuh kembali ’’genderang perang’’ terhadap kesesetan budaya kehidupan sekarang ini.Pembangunan budaya tandingan di hadapan kerakusan, ambisi, dan nafsu yang menjebak Indonesia dalam label korupsi dan penyelewengan sosial serta degradasi moralitas kebangsaan kita merupakan proyek terpenting sekarang ini.
Namun, tanpa radikalisasi tindakan dalam kerangka ini budaya alternatif yang menjamin kelayakan hidup masyarakat tidak akan merembes ke dalam ruang kekuasaan. Maka, sebuah pertobatan dan rasa mawas diri dalam budaya sosial politik tidak boleh tidak menjadi pilihan kita dalam meredam dan menghentikan proses perampingan pada keindonesiaan guna mewujudkan welfare state.
Ini niscaya adalah sebuah jalan kembali yang radikal ketika kehidupan, politik, kekuasaan, ekonomi, dan ruang perbincangan sosial setiap hari diterangi kejujuran, kesederhanaan, kesetiakawanan, antikekerasan, perdamaian dan keadilan. Jika rakyat selamanya terpuruk dan tak beranjak dari kemiskinan akut, bukan sesuatu yang tidak mungkin rakyat akan balik melawan dan menafikan Indonesia sebagai sebuah identitas kebangsaan dan kenegaraannya.
Menguatnya dan melemahnya sebuah negara dan bangsa meminjam perspektif Francis Fukuyama adalah sejauh mana berfungsinya peran negara dalam mengayomi dan memfasilitasi rakyatnya untuk mencapai kehidupan yang layak (State Building: Governance and World Order in the 21st Century, 2004 ). Kesejahteraan adalah kunci menuju kuat dan solidnya sebuah negara bukan mapan dan berdiri angkuhnya sistem kekuasaan.
Apalah artinya sebuah sistem jika tidak becus mengolah dan mengurusi rakyatnya? Tiba saatnya kita membangun Indonesia baru jilid III, (jika kita sepakat revolusi kemerdekaan kita sebagai Indonesia jilid I dan reformasi sebagai Indonesia jilid II). Kesejahteraan dan kemakmuran mesti dijadikan basis kekuatan negara untuk membangun peradaban. Jangan jadikan lengkingan kemelaratan, kegetiran hidup rakyat sebagai angin senja bagi tuan-tuan yang berkuasa.
Tulisan ini pernah dimuat di haria Media Indonesia, 28 Mei 2007.